Bukan Matahari
 |
| Ilustration: Bukan Matahari |
Oleh: Aveus Har
Ema sudah muak. Kenapa ibu selalu membandingkan dirinya dengan gadis jenius itu? Kenapa tidak bisa mengerti betapa dia selalu berusaha menjadi yang terbaik namun kemampuan otaknya terbatas?
Ema memandangi foto yang terpampang di lembar profil siswa majalah sekolahnya. Foto itu memajang gambar Diana yang tengah disalami pejabat dinas pendidikan. Dia tak perlu membaca ulasan yang menyertai. Ema tahu, bahkan mungkin lebih tahu dari reporter majalah “Mekar” ini. Karena sudah belasan tahun Ema mengenal Diana.
Diana Nastiti. Gadis hitam manis yang pendiam. Rumahnya hanya dua ratus meter dari rumah Ema. Ibu Diana seorang guru SMA dan ayahnya seorang dosen. Sewaktu kecil dulu, Ema dan Diana suka main bersama. Namun, sejak SMP, mereka tak lagi dekat. Meski begitu, setiap kabar Diana masih selalu Ema ikuti. Bahkan tingkah dan gayanya. Karena sejak dulu dia ingin “seperti” Diana.
“Lihat Diana, dia anak rajin, tekun…,” selalu seperti itu kalimat yang Ema dapat dari ibunya. Kalimat yang membuatnya merasa dipaksa untuk berhadapan dengan cermin cekung dan bayangannya tampak begitu kecil.
Ema menutup majalah sekolah yang baru saja dia dapat dari sekretaris kelas. Beberapa teman lain masih asyik menyimak halaman majalah intra sekolah itu. Masih membicarakan isi majalah yang menjadi kebanggaan sekolah mereka. Tapi selera Ema telah menguap.
Tadi pagi ibunya kembali membicarakan tentang Diana. Tentang prestasinya yang berhasil lolos dalam seleksi peserta olimpiade matematika tingkat provinsi itu.
Yang kemudian akan bertarung di tingkat nasional. Dan jika lolos lagi, yang mana diyakini semua siswa pasti akan lolos, Diana akan berlaga di tingkat internasional. Hebat!
Dan rasanya… Ema sudah muak. Kenapa ibu selalu membandingkan dirinya dengan gadis jenius itu? Kenapa tidak bisa mengerti betapa dia selalu berusaha menjadi yang terbaik namun kemampuan otaknya terbatas?
Ema menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi, bersamaan Tania yang duduk di sebelahnya. Gadis yang selalu ceria. Yang menikmati masa remajanya seperti tanpa beban. Yang tidak memiliki ambisi meraih juara kelas.
“Karena aku tahu otakku kemampuannya cuma segini,” begitu Tania pernah berkata.
“Dan orangtuamu?”
“Kenapa memang? Mereka tak pernah memaksaku. Yang penting bagi mereka, aku selalu bersungguh-sungguh dalam bidang yang aku sukai.”
“Melukis?”
“Salah satunya.”
Kenapa ibu tak membandingkannya dengan Tania saja? Setidaknya, peringkatnya di sekolah terpaut beberapa level di bawah Ema yang masuk duapuluh besar!
Tania membuat Ema iri. Tania bisa bebas memilih kesukaannya. Sementara dia? Ketika ibu tahu Ema mengikuti kelas teater sebagai kegiatan ekstra sekolah, ibu mencak-mencak.
“Apa yang bisa diharapkan dari kegiatan seperti itu? Mau sok jadi artis?”
“Pagi-pagi makan pecel, nih,” kata Tania membuat Ema menoleh.
“Siapa?”
“Kamu,” senyum Tania dikulum, “Pagi-pagi mukanya kucel.”
Ema meringis. Dia bersyukur memiliki teman duduk seperti Tania. Gadis bermata sipit itu selalu bisa memancing tawa dengan gurau-guraunya.
“Kalau masalah belum mengerjakan pe-er, tidak perlu memasang muka kucel. Setidaknya, aku sudah mengerjakannya,” lanjut Tania.
“Bukan masalah itu,” sahut Ema. “It’s about Diana.”
Tania tersenyum lebar. “Lagi?”
“Yeah… dan rasanya, aku ingin meminta Tuhan menukar tempatku dengan Diana. Biar gadis pendiam itu saja yang menjadi anak ibuku,” ujar Ema.
“Nggak bakalan mau.”
“Ibuku? Oh-ho, dia fans berat Diana, tahu?”
“Maksudku, ibunya Diana nggak mau anaknya diganti kamu.”
Ema nyengir.
“Eh, pengumuman casting kapan?” tanya Tania, mengalihkan pembicaraan. Membuat Ema teringat bahwa pagi tadi ketika bangun dia sudah bersemangat untuk segera mengetahui hasil pemilihan peran pentas teater di pensi tiga bulan depan.
Memang, sekali pun ibunya tak menyetujui kegiatan teater Ema, gadis itu masih teguh pada hobinya. Dalam teater Ema merasakan kenikmatan menjadi sosok-sosok lain yang terkadang bertolak belakang dengan dirinya.
“Lakukan yang terbaik menurutmu, Ema. Bukan menurut orang lain, bahkan ibu kamu,” begitu dorongan moral dari Tania. Sahabat yang sangat mengerti dirinya. Sahabat yang selalu mendorongnya meraih mimpi.
“Tapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Sesuatu yang dilakukan dengan senang hati dan sungguh-sungguh, insya Allah akan terwujud.”
Pentas untuk pensi nanti berjudul “Cindetralala”, sebuah parodi dari kisah klasik Cinderela. Ema sudah menyiapkan diri jauh hari untuk peran ini. Dia ingin menjadi Cinderela.
Dan hari ini pengumumannya!
Yess!!!
Ema mengepalkan tangannya. Usahanya tekun berlatih selama ini tidak sia-sia. Pengumuman yang dipasang di papan informasi menerakan namanya sebagai pemeran utama.
“Selamat ya, Ema,” ucap teman-teman Ema. Gadis itu menyambut dengan senyum bahagia. Kebahagiaan yang tidak ingin dia cemari dengan ingatan pada ibunya. Saat ini, seluruh aliran darah Ema terasa mengalir dengan lancar. Kepenatan yang sempat menelusup terusir dari benaknya.
“Kamu memang hebat,” Tania menyalami.
“Thanks. Tapi masih lebih hebat Diana, kan?”
“Weirdy?”
“Heh, dia sahabatku!” Ema tak suka. Entah siapa yang memulai julukan yang akhirnya berkembang itu.
“Sorry, kebiasaan dengar nama itu disebut daripada nama asli,” sesal Tania.
Mereka melangkah meninggalkan papan informasi. Dalam setiap perjalanan, beberapa teman masih mengucapkan selamat pada Ema.
Di depan ruang guru, mereka bertemu Diana yang baru saja keluar dari ruangan itu. Seperti biasa, gadis itu selalu menunduk ketika berjalan. Sebetulnya Diana cukup manis. Namun mukanya tak pernah cerah. Gayanya juga kaku. Mungkin karena itu dia dijuluki ‘Weirdy’, Diana yang weird. Namun bagaimana pun, Ema tetap merasa Diana sahabatnya meski sekarang mereka tidak pernah lagi bersama.
Tentu saja, karena kesibukan Ema dan Diana jauh berbeda!
“Di!” Ema memanggil. Diana menoleh. Di tangannya terjinjing dua buah buku tebal. Buku yang melihat ketebalannya saja sudah bikin Ema mual.
“Selamat, ya,” salam Ema. “Sorry, telat ngucapinnya.”
“Makasih, Ema,” sambut Diana. “Selamat juga buat kamu.”
Ema meringis. “Tak seberapa dibanding lolos seleksi olimpiade tingkat provinsi.”
Diana tersenyum. Namun senyumnya seperti garis kaku di bibirnya. Mereka melangkah beriring menelusuri koridor. Dalam perjalanan, keterdiaman lebih banyak menyelimuti.
“Ema,” panggil Diana sebelum mereka berpisah di pertigaan koridor karena kelas mereka berbeda. Ema menoleh. “Kamu masih suka ke pantai?”
Ema mengangguk. Dia dan pantai adalah pasangan tak terpisahkan. Bagi Ema, pantai adalah tempat kebebasannya. Tempat di mana dia menemukan kedamaian. Menikmati ombak yang saling bekejaran seolah menikmati fragment kehidupan manusia yang selalu berlomba menjadi yang pertama.
“Nanti sore, maukah mengajakku?”
“Tentu saja, tapi… aku tak berani,” jujur Ema. Sejak ayah Diana memarahinya karena mengajak gadis itu bermain, dulu di awal SMP, Ema trauma. Dia tak mau lagi mengajak Diana. Dia menyadari dunia mereka berbeda. Diana anak pintar yang hari-harinya penuh dengan belajar. Sedang dia gadis hiper yang tak betah diam!
Diana mengangguk, mengerti. Kemurungannya terasa kian kental.
“Aku yang akan menemuimu di pantai.”
Langit sore tidak sebenderang siang tadi. Jelaga tipis menyelimuti awan-awan biru, membuatnya tampak kusam. Diana membiarkan kaki telanjangnya dijilat air yang membuih. Matanya tak lepas dari cakrawala.
Sore ini harusnya dia mengikuti les.
Namun gadis itu sengaja melarikan diri dari rutinitasnya. Meskipun ayahnya akan marah karena perbuatan ini.“Aku capek, Ema. Rasanya aku tak lagi menjadi manusia,” keluh Diana. “Aku iri sama kamu.”
Ema bergeming di samping sahabatnya itu. Betapa hidup ini terasa aneh. Diana yang menjadi obyek keirian Ema karena kecerdasan otaknya justru iri padanya. Pada gadis yang selalu dibandingkan dengan Diana oleh ibunya.
“Tapi kamu harusnya bangga, Di. Berapa siswa di kota kita yang bisa mewakili provinsi di olimpiade matematika itu? Satu. Cuma kamu.”
“Tapi aku tak bisa menikmatinya, Ema. Setiap hari aku harus bergulat dengan angka-angka. Setiap hari harus belajar agar prestasiku tak menurun. Aku bukan robot, Ema.”
Ema tergugu. Waktu yang terentang dan kebersamaan mereka yang hilang beberapa tahun terakhir nyaris membuatnya lupa bahwa Diana sejak dulu tersiksa dengan harapan orangtuanya. Sejak dulu Diana mengeluh bahwa dia merasa hanya boneka yang dikendalikan. Hanya robot yang dijejali program.
“Rasanya aku ingin pergi. Pergi jauh… dan berada di suatu tempat, di mana aku bisa menjadi diriku. Menjadi gadis belasan tahun yang rindu pada kebebasan….”
Ema tak tahu harus berkata apa. Ketika langit kian gelap, dia mengajak Diana pulang. Diana bersikeras akan tinggal.
“Aku akan menikmati hujan.”
Padahal dia tahu, hujan menjadi musuh bagi tubuh ringkih Diana. Ema tak tega memaksa. Ketika hujan turun kemudian, dia melepas jaketnya dan memakainya sebagai payung mereka berdua.
Ema memandangi foto yang terpampang di lembar profil siswa majalah sekolahnya. Foto itu memajang gambar Diana yang tengah disalami pejabat dinas pendidikan. Dia tak perlu membaca ulasan yang menyertai. Ema tahu, bahkan mungkin lebih tahu dari reporter majalah “Mekar” ini. Karena sudah belasan tahun Ema mengenal Diana.
Diana Nastiti. Gadis hitam manis yang pendiam. Rumahnya hanya dua ratus meter dari rumah Ema. Ibu Diana seorang guru SMA dan ayahnya seorang dosen. Sewaktu kecil dulu, Ema dan Diana suka main bersama. Namun, sejak SMP, mereka tak lagi dekat. Meski begitu, setiap kabar Diana masih selalu Ema ikuti. Bahkan tingkah dan gayanya. Karena sejak dulu dia ingin “seperti” Diana.
“Lihat Diana, dia anak rajin, tekun…,” selalu seperti itu kalimat yang Ema dapat dari ibunya. Kalimat yang membuatnya merasa dipaksa untuk berhadapan dengan cermin cekung dan bayangannya tampak begitu kecil.
Ema menutup majalah sekolah yang baru saja dia dapat dari sekretaris kelas. Beberapa teman lain masih asyik menyimak halaman majalah intra sekolah itu. Masih membicarakan isi majalah yang menjadi kebanggaan sekolah mereka. Tapi selera Ema telah menguap.
Tadi pagi ibunya kembali membicarakan tentang Diana. Tentang prestasinya yang berhasil lolos dalam seleksi peserta olimpiade matematika tingkat provinsi itu.
Yang kemudian akan bertarung di tingkat nasional. Dan jika lolos lagi, yang mana diyakini semua siswa pasti akan lolos, Diana akan berlaga di tingkat internasional. Hebat!
Dan rasanya… Ema sudah muak. Kenapa ibu selalu membandingkan dirinya dengan gadis jenius itu? Kenapa tidak bisa mengerti betapa dia selalu berusaha menjadi yang terbaik namun kemampuan otaknya terbatas?
Ema menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi, bersamaan Tania yang duduk di sebelahnya. Gadis yang selalu ceria. Yang menikmati masa remajanya seperti tanpa beban. Yang tidak memiliki ambisi meraih juara kelas.
“Karena aku tahu otakku kemampuannya cuma segini,” begitu Tania pernah berkata.
“Dan orangtuamu?”
“Kenapa memang? Mereka tak pernah memaksaku. Yang penting bagi mereka, aku selalu bersungguh-sungguh dalam bidang yang aku sukai.”
“Melukis?”
“Salah satunya.”
Kenapa ibu tak membandingkannya dengan Tania saja? Setidaknya, peringkatnya di sekolah terpaut beberapa level di bawah Ema yang masuk duapuluh besar!
Tania membuat Ema iri. Tania bisa bebas memilih kesukaannya. Sementara dia? Ketika ibu tahu Ema mengikuti kelas teater sebagai kegiatan ekstra sekolah, ibu mencak-mencak.
“Apa yang bisa diharapkan dari kegiatan seperti itu? Mau sok jadi artis?”
“Pagi-pagi makan pecel, nih,” kata Tania membuat Ema menoleh.
“Siapa?”
“Kamu,” senyum Tania dikulum, “Pagi-pagi mukanya kucel.”
Ema meringis. Dia bersyukur memiliki teman duduk seperti Tania. Gadis bermata sipit itu selalu bisa memancing tawa dengan gurau-guraunya.
“Kalau masalah belum mengerjakan pe-er, tidak perlu memasang muka kucel. Setidaknya, aku sudah mengerjakannya,” lanjut Tania.
“Bukan masalah itu,” sahut Ema. “It’s about Diana.”
Tania tersenyum lebar. “Lagi?”
“Yeah… dan rasanya, aku ingin meminta Tuhan menukar tempatku dengan Diana. Biar gadis pendiam itu saja yang menjadi anak ibuku,” ujar Ema.
“Nggak bakalan mau.”
“Ibuku? Oh-ho, dia fans berat Diana, tahu?”
“Maksudku, ibunya Diana nggak mau anaknya diganti kamu.”
Ema nyengir.
“Eh, pengumuman casting kapan?” tanya Tania, mengalihkan pembicaraan. Membuat Ema teringat bahwa pagi tadi ketika bangun dia sudah bersemangat untuk segera mengetahui hasil pemilihan peran pentas teater di pensi tiga bulan depan.
Memang, sekali pun ibunya tak menyetujui kegiatan teater Ema, gadis itu masih teguh pada hobinya. Dalam teater Ema merasakan kenikmatan menjadi sosok-sosok lain yang terkadang bertolak belakang dengan dirinya.
“Lakukan yang terbaik menurutmu, Ema. Bukan menurut orang lain, bahkan ibu kamu,” begitu dorongan moral dari Tania. Sahabat yang sangat mengerti dirinya. Sahabat yang selalu mendorongnya meraih mimpi.
“Tapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Sesuatu yang dilakukan dengan senang hati dan sungguh-sungguh, insya Allah akan terwujud.”
Pentas untuk pensi nanti berjudul “Cindetralala”, sebuah parodi dari kisah klasik Cinderela. Ema sudah menyiapkan diri jauh hari untuk peran ini. Dia ingin menjadi Cinderela.
Dan hari ini pengumumannya!
Yess!!!
Ema mengepalkan tangannya. Usahanya tekun berlatih selama ini tidak sia-sia. Pengumuman yang dipasang di papan informasi menerakan namanya sebagai pemeran utama.
“Selamat ya, Ema,” ucap teman-teman Ema. Gadis itu menyambut dengan senyum bahagia. Kebahagiaan yang tidak ingin dia cemari dengan ingatan pada ibunya. Saat ini, seluruh aliran darah Ema terasa mengalir dengan lancar. Kepenatan yang sempat menelusup terusir dari benaknya.
“Kamu memang hebat,” Tania menyalami.
“Thanks. Tapi masih lebih hebat Diana, kan?”
“Weirdy?”
“Heh, dia sahabatku!” Ema tak suka. Entah siapa yang memulai julukan yang akhirnya berkembang itu.
“Sorry, kebiasaan dengar nama itu disebut daripada nama asli,” sesal Tania.
Mereka melangkah meninggalkan papan informasi. Dalam setiap perjalanan, beberapa teman masih mengucapkan selamat pada Ema.
Di depan ruang guru, mereka bertemu Diana yang baru saja keluar dari ruangan itu. Seperti biasa, gadis itu selalu menunduk ketika berjalan. Sebetulnya Diana cukup manis. Namun mukanya tak pernah cerah. Gayanya juga kaku. Mungkin karena itu dia dijuluki ‘Weirdy’, Diana yang weird. Namun bagaimana pun, Ema tetap merasa Diana sahabatnya meski sekarang mereka tidak pernah lagi bersama.
Tentu saja, karena kesibukan Ema dan Diana jauh berbeda!
“Di!” Ema memanggil. Diana menoleh. Di tangannya terjinjing dua buah buku tebal. Buku yang melihat ketebalannya saja sudah bikin Ema mual.
“Selamat, ya,” salam Ema. “Sorry, telat ngucapinnya.”
“Makasih, Ema,” sambut Diana. “Selamat juga buat kamu.”
Ema meringis. “Tak seberapa dibanding lolos seleksi olimpiade tingkat provinsi.”
Diana tersenyum. Namun senyumnya seperti garis kaku di bibirnya. Mereka melangkah beriring menelusuri koridor. Dalam perjalanan, keterdiaman lebih banyak menyelimuti.
“Ema,” panggil Diana sebelum mereka berpisah di pertigaan koridor karena kelas mereka berbeda. Ema menoleh. “Kamu masih suka ke pantai?”
Ema mengangguk. Dia dan pantai adalah pasangan tak terpisahkan. Bagi Ema, pantai adalah tempat kebebasannya. Tempat di mana dia menemukan kedamaian. Menikmati ombak yang saling bekejaran seolah menikmati fragment kehidupan manusia yang selalu berlomba menjadi yang pertama.
“Nanti sore, maukah mengajakku?”
“Tentu saja, tapi… aku tak berani,” jujur Ema. Sejak ayah Diana memarahinya karena mengajak gadis itu bermain, dulu di awal SMP, Ema trauma. Dia tak mau lagi mengajak Diana. Dia menyadari dunia mereka berbeda. Diana anak pintar yang hari-harinya penuh dengan belajar. Sedang dia gadis hiper yang tak betah diam!
Diana mengangguk, mengerti. Kemurungannya terasa kian kental.
“Aku yang akan menemuimu di pantai.”
Langit sore tidak sebenderang siang tadi. Jelaga tipis menyelimuti awan-awan biru, membuatnya tampak kusam. Diana membiarkan kaki telanjangnya dijilat air yang membuih. Matanya tak lepas dari cakrawala.
Sore ini harusnya dia mengikuti les.
Namun gadis itu sengaja melarikan diri dari rutinitasnya. Meskipun ayahnya akan marah karena perbuatan ini.“Aku capek, Ema. Rasanya aku tak lagi menjadi manusia,” keluh Diana. “Aku iri sama kamu.”
Ema bergeming di samping sahabatnya itu. Betapa hidup ini terasa aneh. Diana yang menjadi obyek keirian Ema karena kecerdasan otaknya justru iri padanya. Pada gadis yang selalu dibandingkan dengan Diana oleh ibunya.
“Tapi kamu harusnya bangga, Di. Berapa siswa di kota kita yang bisa mewakili provinsi di olimpiade matematika itu? Satu. Cuma kamu.”
“Tapi aku tak bisa menikmatinya, Ema. Setiap hari aku harus bergulat dengan angka-angka. Setiap hari harus belajar agar prestasiku tak menurun. Aku bukan robot, Ema.”
Ema tergugu. Waktu yang terentang dan kebersamaan mereka yang hilang beberapa tahun terakhir nyaris membuatnya lupa bahwa Diana sejak dulu tersiksa dengan harapan orangtuanya. Sejak dulu Diana mengeluh bahwa dia merasa hanya boneka yang dikendalikan. Hanya robot yang dijejali program.
“Rasanya aku ingin pergi. Pergi jauh… dan berada di suatu tempat, di mana aku bisa menjadi diriku. Menjadi gadis belasan tahun yang rindu pada kebebasan….”
Ema tak tahu harus berkata apa. Ketika langit kian gelap, dia mengajak Diana pulang. Diana bersikeras akan tinggal.
“Aku akan menikmati hujan.”
Padahal dia tahu, hujan menjadi musuh bagi tubuh ringkih Diana. Ema tak tega memaksa. Ketika hujan turun kemudian, dia melepas jaketnya dan memakainya sebagai payung mereka berdua.


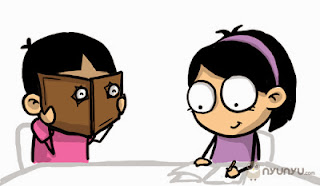
Hai, saya aveus har. Terima kasih untuk mempublikasikan cerpen ini. Omong-omong, cerpen ini ada di buku pelajaran bahasa Indonesia terbitan Yudhistira, dan tak ada yang menghubungi saya.
ReplyDeleteSama-sama. Bila bemar seperti adanya harusnya kamu mendapat royalti dari penerbit karena ia telah menerbitkan karya kamu. Dan sudah sewajibnya mereka menerbitkannya dengan seizin kamu. Coba kamu hubungi kembali dan croscek dengan penerbit buku tsb.
Delete